Malam telanjang. Bulan samar menghilang. Bintang tak peduli, entah ke mana mereka pergi. Angin menghembus bimbang. Udara paruh basah menyaput ruang di tepian lereng bukit Manglayang, Tanah Parahiyangan. Di kolong langit sudut kota Sangkuriang, Bandung, sepasang penghuni bumi, anak-anak Adam, menikam kelam dengan pisau tajam perbincangan. Renungan. Menukik ke kedalaman sanubari. Ya, di sekeping malam Agustusan tepat pada bintik percik tujuh belas, berdimensi waktu: nol titik nol [00.00].
Tengara kala menjadi penting dijelas-uraikan karena terstigma oleh dua lambang yang cukup unik, titik dan nol. Ikon titik berarti henti. Stop. Tak bergerak, dalam konteksnya, tentu. Bagiku hal itu menandai dimensi waktu – seperti yang kutangkap dari kuliah Prof. Erry Amanda kepadaku, malam itu, di kediamannya, kawasan Cibiru [dua anak Adam yang kumaksud di alinea awal adalah aku dan pak Erry]. Waktu tak pernah bergerak. Ia stagnan. Beku. Terhenti. Yang bergerak adalah posisi benda-benda, mengubah tataruang. Bumi yang begerak, berputar pada porosnya, menandai perubahan siang dengan malam, tersebut sehari [dan semalam] yang disepakati oleh dunia ilmu pedngetahuan dalam pembagian jam, menit, detik [sekon]. Pergerakan bumi, bulan, menandai perubahan musim. Pergerakan pemikiran dan tindak manusia menjadikan perubahan lingkungan sosial dan kehidupan. Begitu dan begitu seterusnya. Juga perkembangan rasa estetitka yang merupkana bagian dari imbas perkembangan yang terpersepsi manusia.
Gerak itu disuari oleh perjalanan ‘ruang’ [dalam bidang] dari titik awal menuju akhir dan kembali ke tumpuan semulanya, pada bintik awal. Itulah lambang bilangan ‘kosong’. Tulislah angka nol, yang bermula di start awal menuju garis kian menjauh yang akhirnya kembali ke titik awal. Semakin jauh bergerak meninggalkan posisi awal justru malah mendekati kedudukan semulanya, yakni titik tolaknya dan di situlah terjadi persetubuhan, menyatu diri antara awal dengan akhir. Akhir mencumbu awal. Itulah gerak. Dan silakan mengembangkan dalam diskusi-diskusi khusus tentang malasah ini. Saya di sini sekedar hendak menyatakan keistimewaan dua simbol aksara [bilangan] untuk menstigma dan mengurai makna ‘kemerdekaan bangsa’ dalam renungan di posisi titik 00.00. Begitulah.
Jika waktu tidak bergerak, itu berarti 1945 [dan juga tahun-tahun tonggak perjuangan bangsa sebelumnya: 1908, 1928] tak mengontribusi perubahan apa pun sampai 2017 ini. Sebab, sejatinya, perubahan [sebut: perkembangan] itu ditentukan oleh gerak manusia anak bangsa pemilik bumi pertiwi ini. Apakah gerak yang dilakukan baik secara pribadi, komunal, maupun dalam satu ikatan kosmis kebangsaan, cukup mengarah pada tujuan kemaslahatan masyarakat luas secara keseluruhan, atau hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang berkembang pada kesenjagan di tataran lainnya. Maka wajar apabila penyair dan kritikus sastra [maya] Eko Windarto dalam puisi ‘Riwayat Merah Putih’ menulis ini:
meski hujan sembunyi di dalam hati
kerontang tetap berteduh dalam tubuh
sedang riwayat merah putih memainkan luka hati
kerontang tetap berteduh dalam tubuh
sedang riwayat merah putih memainkan luka hati
Hujan sembunyi, tubuh kerontang, terluka merah putih. Bukan protes, tapi senandung kepedihan. Ya, ya, tak hanya Eko warga Batu, Malang, yang merasakan hal itu. Penyair romantis Handrawan Nadesul pun bersaksi dalam ‘Aku Memikirkan Indonesia’ yang petikannya sbb:
Aku memikirkan Indonesia
Yang terseok kehilangan mata angin
Anak-anak negeri tak lagi memahami nurani
Lupa kalau republik masih di sini
Masih juga kini kita tertatih
Yang terseok kehilangan mata angin
Anak-anak negeri tak lagi memahami nurani
Lupa kalau republik masih di sini
Masih juga kini kita tertatih
Walaupun hanya berpikir [sejatinya di dunia nyata dokter Hans banyak berbuat untuk dunia kesehatan] secara keseluruhan penyair ini masih menyimpan optimisme dan solusi atas kerapuhan negeri dengan ajakan di akhir puisinya:
Mari berikrar wahai segenap anak bangsa
Melakukan sesuatu sejauh-jauh waktu
Demi karena engkaulah kita satu.
Melakukan sesuatu sejauh-jauh waktu
Demi karena engkaulah kita satu.
Artinya, kita memiliki kesadaran untuk keluar dari situasi muram ini dan harus melakukan tindakan kebesamaan, seperti terikrar pada ‘Sumpah 28’. Nah, sejumput laku itulah yang kami tekadkan dalam renungan 00.00 bersama mas Erry Amanda [yang disambut sahabat-sahabat: Ghouts Misra, Pakdhe Agung, Mbah Sastro, Desi Oktoriana, Kek Atek, dll] untuk mengagendakan percikan titik perubahan menuju kemaslahatan lewat dunia kekata di wahana media maya, yang untuk sementara kami tandai dengan nama KULTUR [cyber magazine]. Mohon doa bersama, kan kita mulai suatu langkah awal pembaruan untuk menjawab pertanyaan: apakah kata [literasi] masih berdaya dalam membina spirit perubahan ke kemajuan yang bermaslahat bagi semua.
Itulah hasil renungan kami pada 17 Agustus 2017, yang perlahan kan kami anyam besama para sahabat warga sastra maya. Dan tanpa terasa perbincangan yang seperti berisi beberapa semester kuliahan, berkesudahan [untk sementara] ketika kokok ayam jantan subuh hari menyapa pagi. Aku diantar mas Erry yang mengenakan celana panjang dan sweater warna gelap, menyerupai tanah [mengingatkanku warna asal Adam yang dicipta oleh Allah] sementara aku bercelana green tentara, kaos hijau muda, dan jaket merupa lumut. Hijau warna kehidupan, warna hutan, dan konon juga warna surga. Saya berharap akan menumbuhkan perpaduan ‘manusia sejati’ di ‘jagat bumi’ menyemai kemerdekaan Indonesia. Semoga Tuhan memberkati. Amin.
Cibiru, 17 Agustus 2017
Karya. Sugiono Mpp
















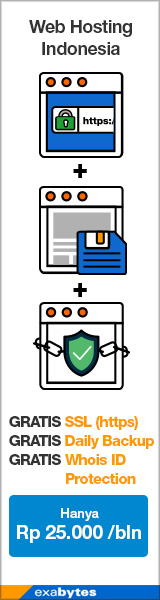
No comments:
Post a Comment